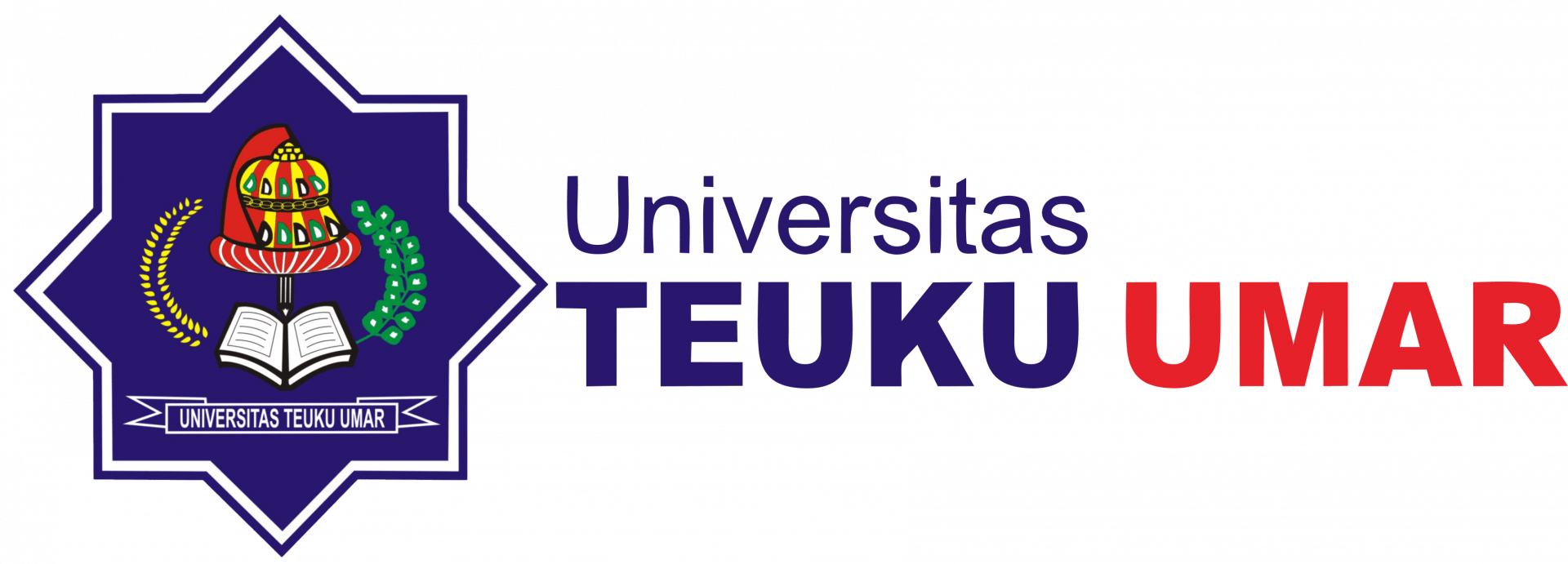Oleh: Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc. (Dosen Pakar SPMI Perguruan Tinggi)
Perbincangan mengenai masa depan pendidikan tinggi di Indonesia semakin relevan di tengah tuntutan global yang kian dinamis. Kualitas lulusan, relevansi kurikulum, dan daya saing institusi menjadi parameter yang tidak bisa lagi dinegosiasikan. Di tengah arus perubahan ini, budaya mutu bukan lagi sekadar slogan, melainkan fondasi krusial yang harus dibangun oleh setiap perguruan tinggi. Regulasi terbaru, seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, memberikan peta jalan yang jelas untuk mewujudkan visi tersebut, mengintegrasikan sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan akreditasi ke dalam satu kerangka hukum yang kokoh.

Regulasi baru ini menandai sebuah evolusi penting dalam cara kita memandang penjaminan mutu. Jika sebelumnya berbagai aturan tersebar, kini semua digabungkan menjadi satu payung hukum, menciptakan efisiensi dan kejelasan. Tujuannya sederhana namun fundamental: meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan. Namun, peraturan saja tidak cukup. Dibutuhkan komitmen dan praktik nyata dari seluruh elemen di perguruan tinggi untuk menggerakkan roda perubahan ini. Inilah saatnya untuk tidak hanya bicara tentang standar, tetapi juga meresapi nilai-nilai budaya mutu ke dalam setiap denyut nadi institusi.
Enam Pilar Budaya Mutu Unggul
Untuk mencapai budaya mutu yang unggul, pemimpin perguruan tinggi perlu fokus pada enam aspek kunci yang membentuk etos kerja dan pola pikir seluruh civitas academica.
- Quality First: Mengutamakan Mutu dalam Segala Hal
Filosofi ini menempatkan mutu sebagai prioritas utama dan tak tergeser. Setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap inisiatif harus berpusat pada upaya peningkatan kualitas. Mutu bukan hanya tanggung jawab tim penjaminan mutu, melainkan mentalitas kolektif yang meresap ke dalam pikiran dan tindakan setiap orang. Dari staf administrasi yang memastikan dokumen mahasiswa rapi, dosen yang merancang materi kuliah yang relevan, hingga pimpinan yang menetapkan kebijakan strategis—semua harus berorientasi pada kepuasan pelanggan, baik internal (mahasiswa, dosen, staf) maupun eksternal (industri, masyarakat, orang tua). Standar SPMI, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan.
- Stakeholder-in: Berorientasi pada Kepuasan Pemangku Kepentingan
Sebuah institusi pendidikan tidak akan bermartabat tanpa pengakuan dan kepuasan dari para pemangku kepentingannya. Perguruan tinggi harus beroperasi dengan kesadaran penuh bahwa seluruh layanannya ditujukan untuk membuat para stakeholder merasa “senang dan gembira.” Ini berarti perguruan tinggi harus peka terhadap kebutuhan pasar kerja, aspirasi mahasiswa, dan harapan orang tua. Kepuasan stakeholder menjadi barometer utama keberhasilan, dan setiap program atau kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap mereka.
- The Next Process is Our Stakeholders: Saling Melayani dalam Ekosistem Pendidikan
Konsep ini menekankan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki “pelanggan” internalnya. Dosen yang selesai mengajar harus melihat mahasiswa sebagai pelanggan. Staf administrasi yang mengurus jadwal melihat dosen sebagai pelanggan. Kepala program studi yang mengevaluasi kurikulum melihat industri sebagai pelanggan. Dengan memetakan proses bisnis, setiap orang dapat mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang harus dilayani, baik yang berasal dari dalam maupun luar institusi. Kesadaran ini menciptakan rantai nilai yang tak terputus, di mana setiap tahapan pekerjaan dilakukan dengan tujuan memberikan kepuasan kepada orang yang akan menggunakan hasilnya.
- Speak with Data: Keputusan Berbasis Data yang Valid
Di era informasi, keputusan tidak bisa lagi didasarkan pada asumsi atau perasaan semata. Budaya mutu menuntut setiap keputusan diambil berdasarkan analisis data yang valid dan reliabel. Dari evaluasi kinerja dosen, efektivitas kurikulum, hingga tingkat kepuasan mahasiswa, semuanya harus diukur dan dianalisis secara objektif. Menggunakan total quality tools atau instrumen sejenisnya dapat membantu perguruan tinggi dalam mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data. Keputusan yang didasarkan pada data faktual akan lebih akurat dan relevan dengan kondisi di lapangan, menghindarkan institusi dari langkah-langkah yang salah arah.
- Upstream Management: Kepemimpinan Partisipatif
Budaya mutu tidak akan berkembang dalam lingkungan yang otoritatif. Sebaliknya, ia tumbuh subur dalam atmosfer partisipatif dan demokratis. Pimpinan perguruan tinggi harus mampu melibatkan seluruh civitas academica dalam proses pengambilan keputusan. Ini bukan hanya tentang delegasi, melainkan pemberdayaan. Pimpinan harus memberdayakan dosen dan tenaga kependidikan (tendik) agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap institusi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang diberdayakan akan lebih termotivasi, kreatif, dan proaktif dalam mencari solusi serta memberikan kontribusi terbaiknya.
- Quality Role and Organization: Organisasi Mutu yang Kuat dan Terstruktur
Terakhir, komitmen terhadap mutu harus diwujudkan dalam kebijakan dan struktur organisasi yang kuat. Perguruan tinggi yang serius ingin mencapai budaya mutu unggul harus memiliki kebijakan mutu yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan bahkan mengadopsi standar internasional. Pimpinan juga harus memperkuat organisasi mutu dengan menyediakan SDM profesional, alokasi dana operasional yang memadai, program sertifikasi auditor mutu internal, dan penerapan sistem digital untuk pengelolaan data. Keterlibatan dalam benchmarking dan adopsi standar internasional seperti ISO akan semakin mengukuhkan posisi institusi di mata dunia.

Dampak Nyata Budaya Mutu Pendidikan Tinggi
Penerapan ke-enam pilar tersebut akan memicu serangkaian transformasi. Pertama, proses sistematis akan terwujud. Perguruan tinggi akan menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi secara terukur. Kedua, perubahan kurikulum menjadi lebih relevan. Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) akan mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menghafal teori, tetapi juga menguasai kompetensi yang dibutuhkan industri. Ini juga mendorong kolaborasi dengan asosiasi program studi untuk menyusun kompetensi lulusan yang selaras dengan kebutuhan pasar. Ketiga, peningkatan akreditasi akan menjadi keniscayaan. Akreditasi bukan lagi beban, melainkan cerminan dari budaya mutu yang telah tertanam. Institusi yang konsisten menjalankan SPMI akan melihat akreditasi program studi dan institusi meningkat, memberikan legalitas dan kredibilitas di mata publik.

Sebaliknya jika perguruan tinggi gagal membangun budaya mutu, konsekuensinya sangat fatal. Minat calon mahasiswa akan menurun, kualitas lulusan merosot, dan kredibilitas institusi akan tergerus. Ketidakpuasan dari mahasiswa dan orang tua akan berujung pada menurunnya daya saing. Di era yang kompetitif ini, stagnasi berarti kemunduran. Perguruan tinggi yang tidak mampu beradaptasi akan tergilas oleh zaman.
Pada akhirnya, membangun budaya mutu bukanlah proyek jangka pendek, melainkan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Ketika SPMI menjadi kuat, akreditasi akan meningkat, prestasi akan menggeliat, dan pada akhirnya, perguruan tinggi akan menjadi institusi yang benar-benar bermartabat.
Editor: Yuhdi F. | Foto: Istimewa